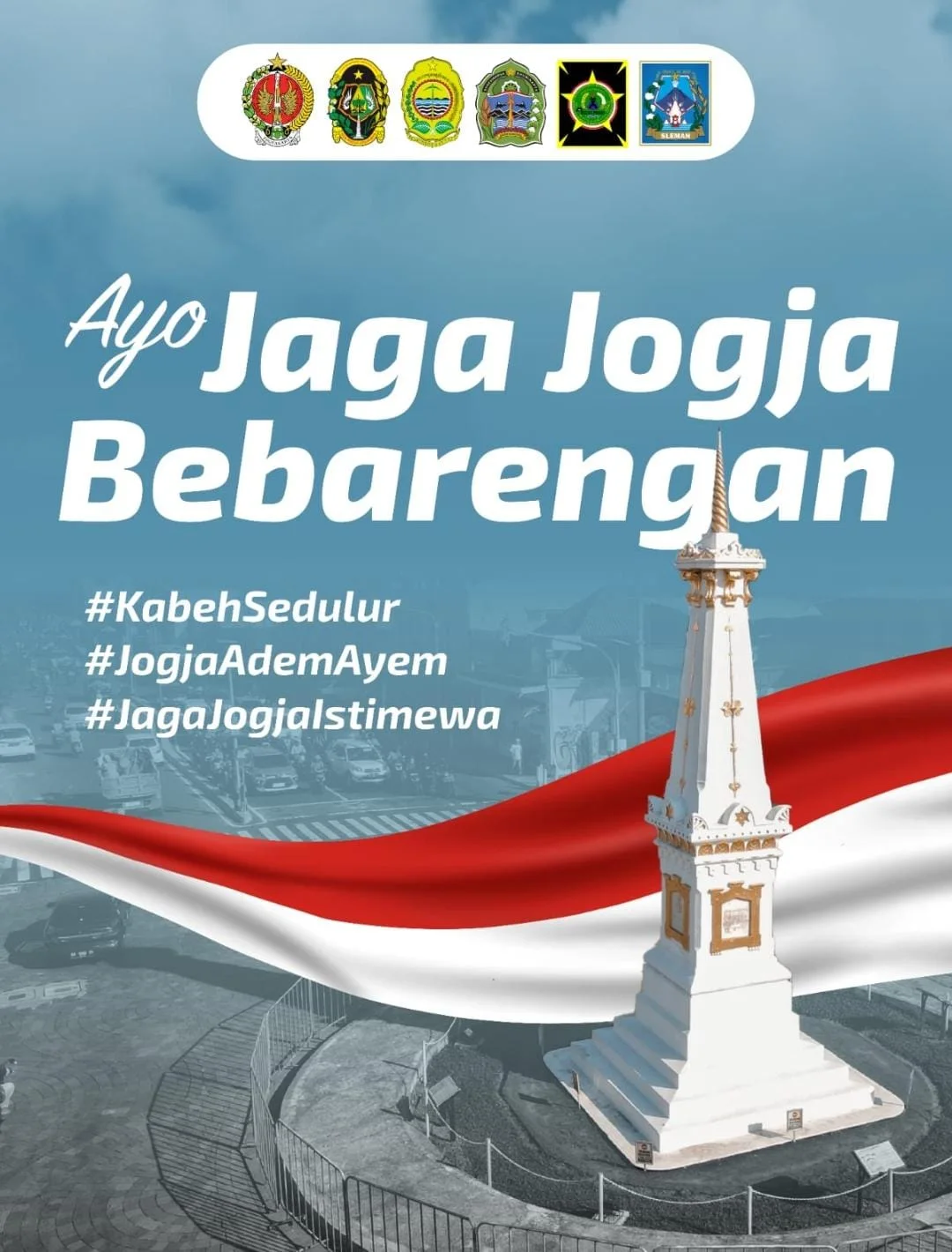Muhammad bin Abdul Wahhab pada masa mudanya merupakan pembelajar melalui perjalanan dan kunjungannya terhadap para ulama Nejd di Hijaz (Makkah-Madinah). Pendiri Wahhabisme ini memungkinkan melakukan hal tersebut karena kekeknya, Syekh Sulaiman bin Ali, merupakan kepala ulama Nejd. Ayahnya, Syekh Abdul Wahhab merupakan tokoh besar yang menjadi qadhi (hakim dalam sistem peradilan Islam)di Uyainah hingga empat belas tahun.
Namun dalam perjalanan intelektualnya itu ia justru mendapat penentangan dari ayah, saudara dan mendapat kritik pula dari para gurunya. Hal ini karena Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kecenderungan mencela praktik-praktik masyarakat muslim dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik. Bahkan, aksi-aksinya tersebut berdampak pada ayahnya yang dipecat dari jabatan sebagai hakim dan terpaksa meninggalkan Uyainah (Ridwan, 2020).
Dalam Sejarah Teror (2011) aliran Wahhabisme erat kaitannya dengan terorisme, ini bermula ketika Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad 18 ingin mengembalikan Islam ke akarnya, karena ia meyakini kaum Muslim telah menjauh dari agama dan ajaran Nabi Muhammad pada masa keemasan Islam. Ia menolak kepercayaan bahwa doa dapat disampaikan melalui orang suci, melarang laki-laki Muslim mencukur jenggot mereka, melarang hari raya, bahkan hari kelahiran Nabi. Pengikut aliran Wahhabisme juga merusak tempat-tempat suci, mengecam kesenian masyarakat. Bahkan, Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan kewenangan pada pengikutnya untuk membunuh, memperkosa, dan merampok mereka yang menolak perintahnya.
Gerakan puritan Wahhabisme itu kemudian banyak digunakan sebagai ideologi kelompok-kelompok terorisme untuk “membenarkan” aksi-aksi mereka yang merenggut ribuan nyawa di berbagai negara. Diantaranya adalah jaringan teroris Al-Qaeda, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), Jabhat al-Nusra, Boko Haram, dan Taliban. (Shukla, A., 2014, Wahhabism and Global Terrorism).
Sesat Pikir Wahhabisme Lingkungan
Tanpa dampak perubahan iklim, hanya sekitar 4% populasi global yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Namun, skenario emisi yang lebih tinggi, dapat menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, mencapai 9,5% hingga 13% populasi dunia pada tahun 2100, yang berarti sekitar 380 juta hingga 520 juta orang (Burzyński et al., 2022).
Sedangkan bencana alam di Indonesia akibat kerusakan lingkungan pada 2023, terjadi 591 bencana tanah longsor, 1.255 bencana banjir, 174 bencana kekeringan, 2.051 bencana karhutla, dan 1.261 cuaca ekstrem. Bencana alam tersebut memakan korban 129 orang meninggal dunia, 155 luka-luka, dan ribuan mengungsi atau relokasi (gis.bnpb.go.id). Kebanyakan dari mereka adalah petani yang gagal panen dan mengalami kekeringan akibat perubahan iklim, orang-orang yang kesulitan air bersih, orang-orang miskin yang rumahnya kebanjiran setiap tahun, juga mereka yang sakit akibat perubahan iklim.
Jika penderitaan umat manusia akibat perubahan iklim belum mampu memantik kesadaran dan kemampuan untuk reboisasi, transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove yang dianggap sebagai “wahhabisme lingkungan” bahkan terasa nihil, setidaknya perlu ada kesadaran untuk menjaga yang masih ada.
Untuk itu Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik Laudato si’ pada 2015 yang berfokus pada masalah lingkungan hidup, perubahan iklim, dan bagaimana umat manusia seharusnya merespons tantangan ekologis yang semakin mendesak. Paus Fransiskus mengajak umat Katolik dan seluruh umat manusia untuk merenungkan tanggung jawab terhadap ciptaan dan menjaga bumi sebagai rumah bersama, terkhusus bagi mereka Kaum Lemah, Miskin, Tersingkir, dan Difabel (KLMTD) sebagai kelompok paling rentan dari perubahan iklim dan bencana alam.
Paus Fransiskus menekankan bahwa krisis lingkungan bukan hanya masalah ekologi tetapi juga masalah sosial dan moral. Ia mengkritik pola konsumsi yang berlebihan, ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa manusia bukanlah penguasa atas bumi, tetapi pelindungnya. Alam dan manusia saling bergantung, dan kerusakan pada alam akan membawa dampak buruk bagi umat manusia itu sendiri, terutama yang paling miskin dan rentan.
Pesan penting dalam Laudato si’ adalah seruan pertobatan ekologis. Melalui pertobatan ekologis, Paus Fransiskus mengajak setiap individu dan masyarakat untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap bumi. Hal ini termasuk perubahan gaya hidup sehari-hari, seperti mengurangi pemborosan energi, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dan lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong keberlanjutan ekologis.
Bumi dalam Laudato si’ digambarkan sebagai Ibu Pertiwi, yang memelihara dan mengasuh umat manusia, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan (Laudato si’ No. 1). Ibu Pertiwi sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya.
Kita berpikir bahwa kita adalah tuan dan penguasa yang berhak untuk menjarah Ibu Pertiwi. Kita telah melupakan bahwa kita sendiri berasal dari debu tanah; tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi, dan udaranya memberi kita nafas serta airnya menghidupkan dan menyegarkan kita (Laudato si’ No. 2).
Benarkah tambang untuk kemaslahatan umat, jika mereka yang terpinggir dan lemah justru menjadi korban. Pendidikan rakyat penambang tetap tertinggal. Air, udara, dan laut tercemar hingga ke organ tubuh. Bencana akibat kerusakan lingkungan juga sudah dialami generasi kini. Akankah kita mewariskan rumah yang lebih membawa penderitaan bagi generasi penerus.***
Bara Wahyu Riyadi, S.E., M.M
Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pemuda Katolik Komda Daerah Istimewa Yogyakarta
Mengelola Penerbit Sembada & Sembada Academy